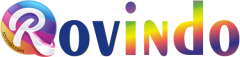armin mustamin toputiri
”BACALAH buku berbeda. Jika kamu membaca buku yang sama dibaca semua orang, maka kamu akan berfikir tak lebih sama semua orang”.
—
PAMBUSUANG, kampung kecil di pesisir pantai Sulawesi Barat. Asal tau, dari sinilah muasal jejak, dua tokoh penting republik ini. Pendekar hukum, Baharuddin Lopa, juga ex-Rektor Unhas Basri Hasanuddin.
Di sela dua tokoh itu, Pambusuang masih menyisih satu sosok lagi. Meski, orang-orang di sana tak melirik, juga tak mau peduli. Malah mencap, memvonisnya ”timorang”. Sesosok tak waras.
Saya, murni bukan warga di sana — tak pernah bersua sosok itu, selain menyimak kisahnya – justru tergiur menelisiknya dari perspektif berbeda. Laiknya dipesan novelis kawakan asal Jepang, Haruki Murakami. Seperti saya kutip di awal catatan ini.
*
Sosok dicap tak waras itu, akrab disapa Kawendi. Nama disematkan warga dari profesinya, penghela bendi (andong). Telah berpulang, tapi jejaknya melegasi, sebagai misteri.
Kelakuannya, mengungkit ingatan saya pada Florence Nightingale. Gadis berlampu, “The Lady With The Lamp”. Tahun 1854, kala perang di semenanjung Krimea-Ukraina baru saja bubar, dia berkeliling menenteng lampu. Mencari korban, lalu diobati.
Kawendi sama. Kala musim angin Timur tiba — saat angin deras berhembus — tak alpa menunai rutinitasnya. Keliling kampung menenteng lampu strongking (petromaks) yang menyala. Ajaibnya, ditunai siang hari. Meski waktu yang sama, cahaya mentari terik bersinar.
Syahdan, tampaklah tontonan anomali itu. Kawendi, ubahnya aktor. Pelakon antagonis di atas pentas teater. Prilakunya ”devian”, bertentangan nalar umum. Itulah dalih, dirinya dicap tak waras.
*
Bikin gemas, Kawendi geming. Tak peduli, cap ditimpakan. Ia kukuh pada rutinitasnya. Saat ditanyai motifnya, dijawab diplomatis. “Mayagai tau tappa pi’de manini mata allo”. Semua kita, mesti waspada, jangan-jangan matahari tiba-tiba padam.
Diberitau, matahari sendirinya akan padam, jika qiamat telah tiba. Eeh, dia malah terkekeh. “Kalian, rupanya tak tau, dunia ini dicipta Tuhan cara sekejap. Qun, jadilah!” jelasnya. ”Tuhan mencipta dunia, sekali saja. Tak usah menanti keduanya”.
Nah, dari ujaran itu, apakah Kawendi layak divonis tak waras? ”Malam tadi, juga bulan bersinar terang. Ketika hujan turun, bulan segera padam”. Alam gelap gulita. ”Kalian mesti hati-hati, saat gelap setan dan kuntilanak banyak gentayangan. Berupaya menggoda”.
*
Itulah Kawendi, sosok multi-tafsir. Multi-interprerasi. Tak jelas presisi antara waras tak warasnya. Normal, vs ab-normalnya. Mengingatkan saya, pada segelintir orang di banyak literatur. Divonis waras, kian diselami, kian ketakwarasannya tampil. Divonis tak waras, kian diselami, kian kewarasannya muncul.
Socrates, maha guru para filosof terbesar itu, juga di Athena suka keliling kampung. Pakaiannya lusuh, kakinya tak beralas. Dia tak henti bertanya, pada siapa ditemui. Naas baginya, dicap tak waras. Dituduh menghasut kaum muda. Dia divonis hukuman mati, cara dipaksa meminum racun hemlock. Tragis, tapi ajarannya abadi. Sosoknya, dikenang filosof terbesar.
Abu Nawas, lengkapnya Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakam. Di Ahvaz-Persia, dijauhi akibat pemabuk. Sosok kontroversial ini, kelak mewujud penyair nyentrik nan cerdas. Ujung kisahnya, dia penyair sufi. Tiada sanding, tiada tanding, tiada banding. Sajaknya “al-Itiraf” (Pengakuan), tak henti dilantun jutaan santri di pondok-pondok pesantren.
*
Kawendi, bukan filsuf. Namanya, tak ada dalam literatur manapun. Di Google, di Wikipedia, tak muncul. Tapi kelakuannya yang anomali, di siang hari berkeliling kampung menenteng lampu strongking yang menyala, dicap tak waras. Tapi bagi saya, justru itulah dia, diri sejatinya.
Saya datang ke Pambusung, hendak menghikmati misteri itu. Andai Kawendi memang tak waras, cukup saya menindih “undzur ma qoola wa latandzur man qoola”. Lihat apa dikata, tau usah lihat siapa berkata.
Jika sedalamnya, Kawendi hendak didaras, di balik kelakuannya termaktub simbol. Di balik ujarannya, tersyirat metafor. Menyentil siapapun kita, agar menghindar, menjauhi kegelapan. Baginya, hakikat kegelapan adalah ketaknormalan. Godaan negatif banyak mendekat, meski wujudnya absurd.
Lampu strongking yang menyala, dia tenteng siang hari, galibnya cara simbolik mensublimasi kita cara mikrokosmos. Agar, siapapun kita, tak melepaskan diri dari cahaya. Nur penerang dari gulita. Sebab, di kegelapan setan dan kuntilanak banyak gentayangan.
*
Alhasil, meski Kawendi divonis tak waras, tapi takaran saya dia sosok maha penting. Guru pembelajar kehidupan. Sekalipun, sajiannya tak lazim, anomali, ringkih, bahkan antagonis. Tapi, jangan-jangan Kawendi waras. Sebaliknya, justru orang-orang di Pambusuang sana yang tak waras. Sebab siapa waras tak waras, terletak sisi mana, subjek memandang objek.
Tapi, ironisnya lagi, andai saya yang memang tak waras. Kepo, mau ambil peduli pada sosok, sejatinya memang tak waras. Duh, hi hi hi…
Surabaya, 10 Oktober 2019
(Dimuat ulang dari edisi revisi)
Artikel Lampu Strongking di Pambusuang pertama kali tampil pada Ujung Jari.