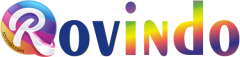MUNCULNYA gagasan pengelolaan tambang oleh kampus menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama terkait dengan prioritas dalam sektor pendidikan. Pendidikan memang diakui sebagai bagian penting dalam pembangunan, namun seringkali ditempatkan sebagai sektor pendukung daripada menjadi fokus utama.
Berdasarkan berbagai sumber yang beredar, salah satu alasan yang mendasari usulan ini adalah manfaat finansial bagi kampus. Disebutkan bahwa dengan adanya pemasukan tambahan dari sektor pertambangan, biaya kuliah mahasiswa dapat dikendalikan sehingga tidak mengalami kenaikan, serta fasilitas akademik dapat ditingkatkan.
Jika benar demikian, tentu hal ini tampak menguntungkan, terutama bagi mahasiswa yang selama ini menghadapi berbagai kendala terkait biaya pendidikan dan sarana kampus. Namun, pertanyaannya adalah apakah kebijakan ini benar-benar bertujuan untuk kepentingan mahasiswa, atau justru memiliki motif lain yang lebih mengarah pada keuntungan institusi?
Dalam beberapa tahun terakhir, mahasiswa kerap melakukan aksi protes terhadap kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan transparansi anggaran kampus. Jika kampus mendapatkan tambahan sumber pendapatan dari sektor tambang, bukan tidak mungkin hal ini juga bertujuan untuk meredam kritik mahasiswa terhadap kondisi pendidikan yang ada.
Perlu diingat bahwa penerapan kebijakan semacam ini harus dikaji secara menyeluruh, mengingat transparansi dan akuntabilitas masih menjadi permasalahan besar dalam berbagai lembaga di Indonesia, termasuk di lingkungan akademik.
Terkait hal ini, kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan dana pun tidak dapat diabaikan. Korupsi bukan hanya terjadi di lembaga pemerintahan atau parlemen, tetapi juga di institusi pendidikan. Ada banyak kasus di mana dana kampus yang seharusnya digunakan untuk kepentingan akademik justru tidak dikelola secara transparan.
Meskipun dalam teori pengelolaan tambang oleh universitas dapat memberikan keuntungan bagi institusi pendidikan, perlu ada jaminan bahwa pendapatan yang dihasilkan benar-benar akan dialokasikan untuk pengembangan fasilitas dan kesejahteraan mahasiswa, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak dalam struktur birokrasi kampus.
Selain itu, usulan ini juga dapat menggeser fokus universitas dari fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan menjadi entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan finansial. Kampus yang seharusnya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi dapat berubah menjadi institusi yang lebih mengutamakan aspek ekonomi dibandingkan akademik. Jika hal ini terjadi, maka bukan tidak mungkin mahasiswa hanya akan dijadikan bagian dari sistem bisnis yang dibangun, tanpa adanya manfaat akademik yang maksimal bagi mereka.
Lebih jauh lagi, perlu dipertanyakan pula apakah mahasiswa saat ini sudah memiliki kesiapan dan kompetensi untuk terlibat langsung dalam pengelolaan tambang. Meskipun beberapa mahasiswa telah memiliki pengalaman magang di sektor pertambangan, mereka tetap masih dalam tahap pembelajaran dan belum memiliki keahlian setara dengan tenaga profesional di industri.
Jika kampus benar-benar diberikan wewenang dalam pengelolaan tambang, perlu dipastikan bahwa mahasiswa yang terlibat mendapatkan pelatihan yang memadai dan perlindungan hukum yang jelas agar tidak hanya dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah tanpa kepastian regulasi.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, usulan ini memerlukan kajian yang lebih mendalam sebelum benar-benar diterapkan. Jika tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa, maka harus ada mekanisme transparansi yang ketat dalam pengelolaan dana serta pengawasan independen untuk memastikan bahwa universitas tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga akademik.
Tanpa adanya sistem pengawasan yang jelas, dikhawatirkan kebijakan ini hanya akan memperburuk permasalahan yang sudah ada dan semakin menjauhkan dunia pendidikan dari esensinya sebagai tempat pengembangan ilmu dan karakter mahasiswa. (mg6)